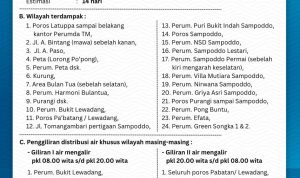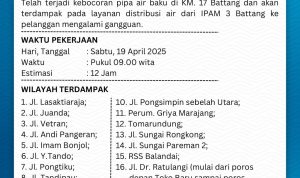Oleh Ir. Irbar Pairing Senobua, MT.
Palopo 1974-1977. Memasuki usia sekolah di SMP. Tepatnya SMP Negeri Palopo. Sekarang lebih dikenal dengan SMP Negeri 1 Palopo. Alamatnya, dulu bernama Jalan Imam Bonjol. Sekarang Jalan Andi Pangerang. Di SMP saya diterima di kelas 1B. Sekelas dengan karibku sejak kecil, Andi Akrab. Dan juga Hartati Amir yang waktu itu tinggal di Jalan Manennungeng. Teman-teman sekelas waktu itu, menunjuk saya sebagai ketua kelas. Amanah sebagai ketua kelas, saya emban hingga kelas tiga.

Aktifitas keseharian seusai jam sekolah, tetap saja seperti waktu masih SD. Selain bermain berenang di sungai kecil yang ada di sepanjang Jalan Opu Tosappaile, juga masih tetap sesekali ke Sungai Boting di belakang rumahnya Opu Sultani. Untuk bermain sepakbola, saya dan teman-teman sepermainan lebih memilih di arena pacuan kuda. Lokasi pacuan kuda, kini menjadi Stadion Lagaligo.
Tidak jarang, seusai bermain bola terjadi keributan. Keributan ini terkadang berlanjut untuk bertemu pada malam harinya. Pertemuan di malam hari, biasanya dipilih lah Lapangan Gaspa. Dan pertemuan di Lapangan Gaspa ini berahir dengan aksi kejar-kejaran, dan sekaligus bubar dengan sendirinya, karena masing-masing pulang ke rumahnya. Esok harinya, bermain bola lagi. Keributan semalam sudah dilupakan. Begitu seterusnya. Keributan di lapangan bola, berlanjut pada malam hari, dan selesai dengan sendirinya setelah kejar-kejaran dan masing-masing pulang ke rumahnya.
Pernah juga kami janjian untuk bermain bola di Pantai Labombo. Waktu itu Pantai Labombo memberikan suasana yang nyaman serta indah dipandang mata. Pasirnya putih bersih. Airnya jernih. Bermain bola di kawasan Pantai Labombo, waktu terasa cepat berlalu. Rasa-rasanya baru beberapa menit bermain, sudah harus segera diakhiri. Keringat pun rasa-rasanya belum tuntas membasahi tubuh, namun permainan bola sudah harus dihentikan. Gelap mulai menyelimuti bumi. Bola kadang mulai samar-samar terlihat. Bermain bola di Pantai Labombo terasa tak pernah puas. Kepingin dan kepingin lagi untuk melanjutkannya di esok hari.
Pemandangan di Pantai Labombo memang tak seseram namanya. Pantai ini diberi nama labombo, karena konon banyak bombo alias setan yang bergentayangan di malam hari. Menurut cerita, di Pantai Labombo ini dulunya pernah menjadi markas para pejuang kemerdekaan. Dari pantai ini memang terlihat dengan mudah untuk memantau pergerakan kapal-kapal. Baik kapal yang sedang melintasi Teluk Bone, maupun mengamati dari jauh kegiatan bongkar muat kapal yang sedang sandar di Dermaga Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo.
Walau sangat strategis untuk memantau pergerakan kapal-kapal yang lalu lalang, namun ternyata juga beresiko sangat mudah untuk dilihat dari arah laut. Sekali waktu, kapal perang milik penjajah Belanda yang ingin sandar di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo mencurigai adanya aktifitas di Pantai Labombo ini. Setelah mendekat dan dalam jarak yang terjangkau oleh senjata mereka, tentara penjajah itu menembaki para pejuang. Nyaris seluruh pejuang yang bermarkas di Pantai Labombo waktu itu tewas oleh musuh. Itu lah awal mula dinamainya Pantai Labombo. Karena menurut cerita, masih bergentayangan arwah-arwah para pejuang yang tewas oleh tantara musuh tersebut.
Tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Ringgit, juga ada satu tempat yang pernah saya kunjungi. Yakni Pulau Libukang. Waktu itu dalam rangkaian kegiatan organisasi filateli, kumpulan orang-orang yang hobby mengumpulkan prangko, Persatuan Filateli Indonesia. Kami melakukan kunjungan wisata ke pulau ini. Di pulau yang berjarak sekitar dua kilometer dari dermaga Pelabuhan Tanjung Ringgit, hanya dapat dijangkau dengan perahu bermotor. Butuh waktu kurang lebih satu jam untuk sampai ke pulau ini.
Pulau Libukang ini ternyata tidak lah terlalu luas. Bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Untuk mengelilinginya, tidak cukup satu jam kami sudah kembali di titik star. Mungkin hanya sekitar satu kilometer lebih. Atau paling maksimal satu setengah kilometer lah kelilingnya. Menurut catatan yang ada, luasan Pulau Libukang ini ada pada kisaran 8 hektar. Lebarnya mungkin hanya sekitar 200 meter, dari pinggir sebelah timur tempat kita menambatkan perahu hingga ke arah barat. Kemudian dari arah selatan ke utara, panjangnya sekitaran setengah kilometer.
Waktu itu, Pulau Libukang sudah tak berpenghuni. Yang ada di sana, hanya lah sebuah Masjid serta dua kuburan tua. Kuburan ini atas nama Nenek Hwang dan Nenek Poko’. Menurut cerita, Nenek Hwang ini adalah penerima pertama aliran tarekat khalwatiah di Palopo. Jadi Pulau Libukang ini, pernah menjadi pusat pengembangan aliran Tarikat Khalwatiah.
Kebetulan sewaktu kami ke pulau itu, saya juga sedang aktif berlatih mempersiapkan diri untuk mengikuti Jambore Nasional Pramuka di Sibolangit Sumatera Utara, sehingga sempat terbersit dalam pikiran saya, Pulau Libukang ini sangat bagus untuk dijadikan lokasi perkemahan Pramuka untuk tingkat Kabupaten Luwu. Waktu itu, Kabupaten Luwu masih menyatu dari Larompong di selatan hingga Mangkutana di utara dan Soroako di bagian timur. Menyangkut keberangkatan saya sebagai peserta Jambore Nasional di Sibolangit akan saya ceritakan dalam tulisan tersendiri.
Kemudian tentang Pelabuhan Tanjung Ringgit yang merupakan satu-satunya akses untuk menuju Pulau Libukang. Menurut catatan yang ada, pelabuhan ini dibangun sejak Tahun 1920. Masih dalam masa penjajahan Belanda. Sewaktu kami mengunjungi Pulau Libukang, kapal yang sandar atau sedang berlabuh di pelabuhan cukup ramai. Ukurannya pun beragam. Mulai ukuran besar hingga yang paling kecil.
Waktu itu, mobilisasi penduduk dari ibukota kabupaten ke kecamatan paling utara atau timur, Malili dan Soroako misalnya, masih lebih banyak yang memilih menggunakan kapal dibanding lewat darat. Terutama untuk kalangan pedagang beras dan hasil bumi lainnya, termasuk pedagang sayuran.
Kapal yang mengangkut beras, selain tujuan Malili, juga ada yang tujuannya ke sejumlah kota-kota kecil di Sulawesi Tenggara. Seperti Kolaka, Batunong, dan Lasusua. Bahkan untuk tujuan Kalimantan, Maluku, dan Irian juga ada. Memang cukup ramai Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo saat itu. Bahkan perdagangan langsung antara Palopo dan Surabaya juga masih ada waktu itu. Kapal dari Tanjung Ringgit ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengangkut hasil bumi, seperti beras dan kopra. Dan sekembalinya akan membawa hasil industri untuk kebutuhan bangunan, seperti besi dan semen.
Hanya saja, pemandangan keramaian aktivitas di Pelabuhan Tanjung Ringgit seperti itu sudah tidak terlihat sekarang. Kapal yang terlihat masih ada, hanya lah jenis kapal pesiar dan kapal pengangkut minyak sawit. Butuh perencanaan yang matang dan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk dapat mengembalikan kejayaan Tanjung Ringgit, setara dengan dua pelabuhan tanjung lainnya, yakni Tanjung Periok Jakarta, dan Tanjung Perak Surabaya. Di sinilah pentingnya toleransi holistik, toleransi di segala aspek untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna demi kemakmuran masyarakat.(*)